Aku tidak mau “mupus”: menganggap tak ada sesuatu yang sebenarnya
masih mengendap di dasar jiwa. Pura-pura tidak melihat ada sekam di
ruang gelap batin bangsaku. Yang sewaktu- waktu akan menyala jadi api,
meskipun hari ini sedang seakan-akan mereda.
Maka aku terus bertengkar melawan tiga aku-ku. Biarlah aku berempat
menjadi kubangan api, untuk turut bersedekah menyerap bara api dari jiwa
gelisah bangsaku.
Pada 17 Ramadlan tahun-2 Hijriyah, Kanjeng Nabi melansir terminologi yang luar biasa: “Kita baru menyelesaikan perang kecil, dan sekarang kita masuki perang besar”.
Padahal Perang Badar yang barusan usai, sedemikian dahsyat. Suatu
pertempuran di mana Allah “melanggar” segala Ilmu Militer manusia dan
“mengejek” semua logika peperangan.
Sedangkan aku yang hanya berempat, tak pernah selesai bertengkar
memperebutkan siapa di antara kami yang “aku nafsu”, siapa “aku iman”.
Yang mana “aku kegelapan” dan “aku tercerahkan”. Bagaimana mempetakan
aku-benar aku-salah aku-baik aku-buruk aku-pecinta aku-pembenci, juga
aku-mengAllah aku-memberhala.
Bisa dibayangkan semrawutnya ribuan “aku” dalam atlas Bhinneka Tunggal Ika:
tuding menudingnya pasti jauh lebih gaduh. Sekam-sekam permusuhan,
kebencian dan rasa tidak aman, tak pernah benar-benar padam. Bahkan
senyatanya: “perang besar melawan nafsu” itulah sejatinya pilar bangunan
Bangsa dan Negaraku.
313 prajurit Badar, dengan kualitas personil yang tidak memadai
secara militer, dan peralatan perang yang sangat minimal, menang melawan
1.200 pasukan Sekutu, dengan rumus yang tidak pernah disebut oleh Buku
Perang zaman apapun. Yakni “Innama tunshoruna wa turhamuna wa turzaquna bidlu’afaikum”: Kalian dilimpahi pertolongan, kemenangan dan rizki oleh Allah, karena kalian maju perang demi membela rakyat yang dilemahkan.
Muhammad Saw “nekad” menjanjikan rumus itu ketika berpidato di depan
pasukan Badar sebelum pertempuran. Beliau tahu itu irrasional bagi
logika manusia dan kehidupan di dunia. Maka kepada Allah beliau
menyampaikan pernyataan: “In lam takun ‘alayya Ghodlobun fala ubali”:
Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, wahai Kekasih, hamba tak peduli
pada nasib hamba di dunia. Hamba ikhlas kalah, hancur dan mati — “asalkan Kekasih tidak marah kepadaku”.
Dan ternyata dimensi hubungan cinta dengan “harga mati” semacam itu yang membuat Sang Kekasih melimpahkan kemenangan.
Tetapi, di antara aku berempat ini: yang mana yang dilimpahi kemenangan, dan yang mana yang dimurkai?
Aku berkata kepadaku: “Aku justru sangat tahu bahwa sebenarnya tak
ada masalah dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Islam, Khilafah,
Pluralitas, Toleransi dan semuanya. Itu semua hanya diperalat untuk
proses adu-domba demi mencapai kepentingan suatu golongan. Sejarah
Bangsa Indonesia dikacau dan dirusak oleh suatu golongan”
Aku yang di antara khalayak menyodok: “Tapi beberapa kali Sampeyan
menulis sangat serius hal-hal yang menyangkut Pancasila, sehingga kami
mendapat kesan bahwa Sampeyan terseret oleh rekayasa isyu yang
menyebarkan anggapan bahwa ada masalah dengan Pancasila. Padahal sudah
72 tahun Pancasila hidup baik-baik saja”
“Seolah-olah ada ancaman serius terhadap Pancasila
kesepakatan kebangsaan dan kenegaraan kita”, aku yang di depanku
menambahkan, “sehingga di sana sini diselenggarakan peneguhan kembali
tekad terhadap lestarinya Pancasila. Dan yang dianggap ancaman itu
adalah Islam”
Aku yang di depan menambahi, “Bahkan Sampeyan sedang menyiapkan
seri-seri panjang tulisan tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,
hubungannya dengan Agama, Islam, Khilafah, Jawa….”
Aku mempertahankan diri: “Lho aku kenal Pancasila sejak mulai
mengenal huruf di masa kanak- kanak. Dan secara alamiah aku terus
bersabar menjalani proses untuk mematangkan Pancasila kehidupanku.
Karena Pancasila adalah Surat Nikah Kebangsaan yang aku berada dan terikat di dalamnya, meskipun hanya sebagai rakyat kecil”
Tetapi aku-aku itu terus membombardir: “Tulisan-tulisan Sampeyan
sengaja atau tak sengaja membuat yang membacanya merasa di bawah
sadarnya bahwa bangsa kita sedang mempertengkarkan Pancasila. Bangsa
Indonesia dan Ummat Islam tiba-tiba bergerak menuju anggapan dan
kepercayaan bahwa Pancasila alamatnya di sini, sementara Islam alamatnya
di sana. Bahwa Kaum Muslimin adalah ancaman bagi Bhinneka Tunggal
Ika….”
Karena mereka tak henti-hentinya menyerbu, akupun balik menerjang mereka dengan tiba-tiba bersuara keras, mengaji murottal membacakan Surat At-Tin: “Demi pohon Tin, demi pohon Zaitun, demi Gunung Sinai dan demi Negeri gemah ripah loh jinawi….”
“Apa itu!”, aku yang di khalayak meneriakiku.
“Tin adalah pohon yang tumbuh di wilayah Budha Gautama memproses pencarian hidupnya. Zaitun adalah perkebunan di perkampungan Isa Yesus. Bukit Sinin, Tursina, padang Sinai, adalah arena pergolakan dan perjuangan Musa. AlBalad al-Amin adalah gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo dalam pengayoman Muhammad
saw di Madinah. Hanya karena keseriusan konsep dan hidayah tertentu
Allah bersumpah atas empat hal sekaligus. Peradaban Abad-21 sekarang ini
sedang berjalan lamban menuju awal kesadaran Tin. Perhatikan
kegelisahan hati ummat manusia di Eropa dan Amerika”.
https://www.caknun.com/2017/surat-nikah-kebangsaan/
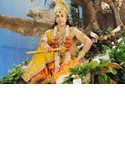








0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas saran & kritiknya !!